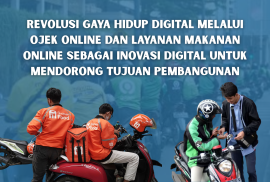Dalam beberapa dekade terakhir, kopi telah bergeser. Bukan hanya sekadar “minuman” tetapi sudah menjadi fenomena budaya dan gaya hidup urban yang kuat. Pertumbuhan coffee shop di kota-kota besar mencerminkan perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan. Kedai kopi saat ini berfungsi sebagai ruang interaksi sosial, tempat kerja alternatif, hingga arena kreativitas bagi pekerja kreatif, mahasiswa, dan generasi muda yang mencari pengalaman berbeda dari sekadar konsumsi kopi biasa. Fenomena ini menggambarkan bahwa kopi sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari ritme kehidupan masyarakat perkotaan dan simbol gaya hidup modern.
Pascasarjana UGM
Dalam era digital yang terus berkembang, buku tidak lagi hanya hadir dalam bentuk cetak tradisional. Buku digital (e-book) telah menjadi bagian penting dari ekosistem pengetahuan global, menawarkan akses cepat dan portabilitas tinggi. Namun, perdebatan mengenai kelebihan dan kekurangan antara buku digital dan buku fisik juga semakin menguat, mencakup aspek pembelajaran, dampak lingkungan, serta kontribusinya terhadap target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 12 (Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab), dan SDG 13 (Aksi Iklim) dan SDG 15 (Ekosistem Darat).
Seiring meningkatnya urbanisasi, kebutuhan terhadap sistem transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan inklusif menjadi krusial tidak hanya untuk mobilitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030. Dalam hal ini, transportasi umum menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan. Transportasi berkontribusi secara langsung pada pencapaian SDG 11 (Sustainable Cities and Communities), yakni menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat. Selain itu, pengembangan transportasi umum yang berkelanjutan juga berdampak positif terhadap tujuan lain, seperti SDG 13 (Climate Action), SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure), dan SDG 3 (Good Health and Well-Being).
Masalah sampah plastik terus menjadi sorotan global. Plastik sekali pakai, terutama botol dan kemasan air, telah mengakumulasi dampak lingkungan jangka panjang, seperti: polusi di darat dan laut, beban tambahan bagi tempat pembuangan akhir (TPA), serta konsumsi sumber daya dan energi yang besar dalam produksi. Salah satu solusi sederhana namun berdampak nyata adalah penggunaan tumbler atau botol minum/wadah minum yang dapat dipakai ulang.
Beberapa penelitian dan program di Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan tumbler dapat secara signifikan mengurangi sampah plastik. Dewasa ini tumbler bukan sekadar tren gaya hidup, melainkan dapat menjadi representasi perubahan perilaku konsumsi menuju keberlanjutan.
Limbah gadget (e-waste) telah menjadi salah satu isu lingkungan paling mendesak pada abad ke-21. Laporan Global E-Waste Monitor mencatat bahwa dunia menghasilkan sekitar 62 juta ton e-waste pada tahun 2022, dan hanya sekitar 22% yang berhasil didaur ulang melalui jalur resmi. Proyeksi menunjukkan angka ini dapat mencapai 82 juta ton pada 2030 jika pola konsumsi teknologi tidak berubah. E-waste adalah limbah kompleks yang mengandung plastik, bahan kimia, serta logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium yang dapat mencemari tanah dan air. Ironisnya, limbah ini juga menyimpan sumber daya bernilai tinggi seperti emas, tembaga, hingga rare earth elements, yang justru sering terbuang karena kurangnya fasilitas dan regulasi daur ulang yang efektif.
Perdagangan pakaian impor, khususnya pakaian bekas, telah menjadi bagian signifikan dari dinamika ekonomi global dan pola konsumsi masyarakat di negara berkembang. Pakaian bekas impor umumnya berasal dari proses donasi massal, pusat daur ulang tekstil, toko retail yang menyisakan deadstock, serta gudang penyalur barang non sortir dari negara-negara maju. Dalam rantai distribusi yang panjang ini, pakaian dikumpulkan dari berbagai sumber, disortir berdasarkan kualitas, kemudian dikompresi menjadi bal-bal besar sebelum dikirim ke negara tujuan. Kompleksitas rantai pasok tersebut menyebabkan asal-usul setiap pakaian sulit dilacak secara individual, sehingga aspek higienitas dan keamanan produk menjadi isu yang perlu dikaji secara ilmiah.
Dalam satu dekade terakhir, kemunculan ojek online dan layanan pesan-antar makanan telah mengubah pola hidup masyarakat Indonesia secara signifikan. Dari sekadar alat transportasi, ojek online kini menjelma menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital yang kompleks, melibatkan jutaan pengemudi, pelaku usaha mikro, hingga konsumen dari berbagai lapisan sosial. Fenomena ini tidak hanya merepresentasikan kemajuan teknologi informasi, tetapi juga menggambarkan dinamika pergeseran sosial-ekonomi baru yang erat kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang cukup melalui penyediaan makanan sehat di sekolah. Lebih dari sekadar pemberian makan, program MBG adalah investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia. Harapannya, dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang fokus, anak-anak dapat tumbuh optimal dan berkontribusi dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.
Dilihat dari perspektif pembangunan berkelanjutan, program MBG menjadi sarana dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama di bidang gizi, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan ekonomi masyarakat. Secara spesifiknya berkaitan dengan SDGs 2 (Zero Hunger), SDGs 3 (Good Health and Well-being), SDGs 8 (Decent Work and Economic Growth), dan SDGs 12 (Responsible Consumption and Production). Program MBG sebenarnya bisa membantu mengurangi kelaparan tersembunyi (hidden hunger) pada anak usia sekolah dengan menyediakan makanan bergizi setiap hari. Hal ini bisa menjadi langkah penting dalam mengurangi angka malnutrisi dan stunting. Dimana dengan adanya akses gizi yang seimbang dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental anak, sekaligus menekan potensi penyakit akibat kekurangan nutrisi. Anak yang tidak lapar cenderung lebih mudah fokus belajar. MBG secara tidak langsung mendukung proses belajar yang produktif, menurunkan tingkat ketidakhadiran, dan meningkatkan hasil akademik. Program ini sebenarnya juga menciptakan efek ekonomi berantai melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal dalam penyediaan bahan makanan. Di sisi lain, MBG dapat menjadi wadah edukasi tentang pola makan sehat dan berkelanjutan, termasuk upaya mengurangi limbah makanan dan mengoptimalkan bahan pangan lokal.
“Ego sektoral lagi, ego sektoral lagi!”
Jengah ketika selalu mendengar alasan mengapa sebuah program dengan ribuan rapat dan triliunan anggaran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ego sektoral selalu dituding sebagai lakon antagonis. Jika keberadaan ego sektoral dibayangkan sebagai sebuah orchestra yang masing-masing musisi memainkan lagu favoritnya di saat yang bersamaan, terdengar berisik, riuh, tak harmonis, tak nikmat, gagal.
Ego sektoral sebagai biang kerok penghambat pembangunan telah disadari sepenuhnya oleh orang nomor satu di Indonesia. Sebut saja, Mantan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Arahan pada awal pemerintahannya, tahun 2015 di dua ruang siding berbeda: Sidang Kabinet dan sidang Tahunan MPR, Presiden terpilih ini sudah memancarkan sinyal anti-ego sektoral. “jangan terjebak ego sektoral, pemerintah harus satu, konsolidasi kementerian/lembaga harus betul-betul selesai”. Masih dengan nada yang sama, “Hilangkan Ego sektoral, apalagi ego kementerian, ego kepala Lembaga”. Pernyataan ini disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara tanggal 9 April 2018. Tujuh tahun sejak pemerintahannya, pernyataan tidak berubah “persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tetapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral. Itulah persoalan kita”, tegas Jokowi saat pidato dalam acara Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit tanggal 9 Juni 2022 di Wakatobi.
Pesantren masih menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat untuk memondokkan anak mereka belajar ilmu agama. Di tengah gempuran pemberitaan negatif mengenai pesantren di media, ternyata jumlah santri di Indonesia terus mengalami peningkatan. Tentu ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab, apakah pesantren masih relevan sebagai tempat pendidikan yang berkualitas di Indonesia? Isu kekerasan baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual sering muncul di media massa dan juga media sosial. Berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pada tahun 2024, sebanyak 36 persen atau 206 kasus kekerasan di lembaga pendidikan terjadi di lembaga pendidikan berbasis agama. Dimana 16 persen atau 92 kasus terjadi di madrasah dan 20 persen atau 114 kasus terjadi di pesantren. Jenis kekerasan yang terjadi bervariasi diantaranya kekerasan fisik, perundungan, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kebijakan diskriminatif. Tingginya tingkat kekerasan di pesantren ternyata tidak menyurutkan masyarakat untuk memondokkan anak mereka di pesantren (Jannah, 2024). Data dari Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah santri di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2023/2024 ke tahun 2024/2025 yaitu sebanyak 5,8 persen atau 512.029 santri. Jumlah santri pada tahun 2023/2024 di Indonesia tercatat sebanyak 8.837.160 santri, sedangkan pada tahun 2024/2025 jumlah santri meningkat menjadi 9.349.189 (Said, 2025).