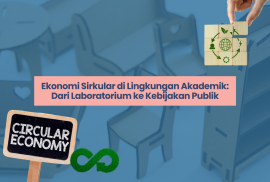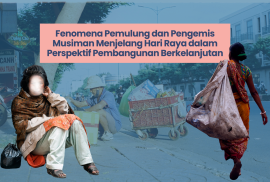Indonesia kini menjadi pemasok penting 9% produksi kopi di dunia rerata 700 ribu ton per tahun setelah produsen Brasilia dan Vietnam (worldstatistic.net, 2024). Problematika negara-negara produsen kopi terkadang serupa namun juga dapat berbeda dan spesifik. Karakteristik identik dari Sumatra, Jawa hingga Papua mempromosikan tradisi minum kopi, gaya hidup hingga bisnis. Gelombang kopi dalam perspektif SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mentransformasi kompleksitas masyarakat hari ini dari berbagai pemangku kepentingan kopi. Tidak hanya rantai mata pencaharian petani kopi, tetapi juga industri pemroses hingga pemasaran, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja hingga produksi dan konsumsi dituntut untuk ramah lingkungan.
SDGs
Komunikasi Reklamasi: Pendekatan Strategis untuk Membangun Ekosistem Pascatambang yang Berkelanjutan
Kasus dan problematika tata kelola industri pertambangan mineral di Indonesia selalu menjadi isu sentral yang sangat menarik perhatian, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dalam konteks keberlanjutan lingkungan dan sosial. Sejak lama Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya mineral yang melimpah. Menurut data United States Geological Survey (USGS, 2023), Indonesia memiliki sekitar 42% dari total cadangan nikel global, serta menyumbang hingga 51% dari produksi nikel dunia. Selain itu, Indonesia merupakan produsen batubara terbesar ketiga secara global dengan kontribusi sekitar 9% terhadap total produksi batubara dunia. Sedangkan di sektor timah, Indonesia menempati posisi kedua sebagai produsen timah terbesar di dunia, dengan hasil produksi mencapai 78.000 ton per tahun, dengan cadangan terukur mencapai 2,8 juta ton atau sekitar 16% dari cadangan global.
Di tengah tantangan global yang sangat kompleks dewasa ini, pendekatan interdisipliner dalam riset menjadi semakin relevan, khususnya dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan SDGs ke-17 menekankan pentingnya kemitraan yang kuat dan inklusif di semua tingkatan untuk mendukung agenda pembangunan yang berkelanjutan. Jika dispesifikkan ke dalam konteks pendidikan tinggi, riset interdisipliner memiliki peluang yang besar untuk mengkolaborasikan keahlian dari berbagai bidang, seperti teknik, ekonomi, kesehatan, sosial humaniora, sains, hingga lingkungan untuk menghasilkan solusi yang lebih holistik dan aplikatif terhadap isu-isu global yang sudah terjadi atau mungkin akan terjadi.
Penerapan prinsip ekonomi sirkular di lingkungan akademik menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kampus yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara ekologis. Ekonomi sirkular menekankan pada pengurangan limbah melalui desain ulang sistem produksi dan konsumsi, dengan prinsip 3R: Reduce, Reuse, dan Recycle. Dalam konteks kampus, limbah dari laboratorium, kantin, dan aktivitas mahasiswa sering kali berkontribusi signifikan terhadap degradasi lingkungan, padahal di sisi lain, kampus memiliki kapasitas intelektual dan teknologi untuk menjadi pelopor perubahan. Hal ini sejalan dengan Tujuan SDGs ke-12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dan SDGs ke-11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) yang menuntut lembaga pendidikan turut mengambil peran dalam transformasi sistem konsumsi.
Terjadinya industrialisasi, pertumbuhan populasi yang pesat, dan perilaku konsumtif yang tidak berimbang dengan kepedulian terhadap lingkungan menjadi latar belakang pentingnya penerapan pengolahan sampah rumah tangga. The Atlas of Sustainable Development Goals tahun 2023, Bank Dunia mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 2,2 miliar ton sampah di seluruh dunia dan akan terus meningkat hingga 73% pada tahun 2025. Terjadinya lonjakan tren timbulan sampah di Indonesia yang kini telah menyentuh angka 68,9 juta ton per tahunnya dengan 51% rinciannya berasal dari aktivitas rumah tangga (RT) (KLHK, 2023). Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam upaya pengelolaan limbah rumah tangga secara berkelanjutan karena masyarakat merupakan penghasil dari sampah itu sendiri. Namun, bentuk partisipasi masyarakat dalam program ini masih beragam, mulai dari berpartisipasi dalam bentuk ide, tenaga fisik, dan keterampilan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah peranan budaya kato saio yang berkembang secara alami diantara lingkungan sosial masyarakat Kota Jambi menjadi salah satu faktornya.
Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) semakin nyata dengan terselenggaranya pelatihan literasi digital bagi penyuluh pertanian dan petani milenial. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Fakultas Pertanian UGM, Sekolah Pascasarjana UGM, Universitas Passau Jerman, dan UPTD BPSDMP DIY. Pelatihan bagi penyuluh dilaksanakan pada Jumat, 02 Mei 2025, sedangkan pelatihan untuk petani milenial berlangsung pada 03, 05-07 Mei 2025, bertempat di BPSDMP DIY, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.
Diabetes melitus atau diabetes tipe 2 menjadi epidemi global yang kini marak terjadi dan tidak memandang usia. Diabetes ini merupakan kondisi kronis yang terjadi karena tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan benar sehingga kadar gula darah meningkat. Penyakit ini sering terjadi tanpa gejala yang mencolok di awal. Bahkan, diabetes sering kali tidak terdiagnosis hingga menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan ginjal, kebutaan, bahkan amputasi.

Di Indonesia, berdasarkan data dari Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat (Pusinfokesmas) FKMUI menunjukkan bahwa prevalensi diabetes meningkat signifikan setiap tahun. Penyebabnya adalah pola hidup yang minim aktivitas fisik, pola makan tidak sehat, tinggi konsumsi makanan olahan, faktor keturunan, ataupun stres kronis. Survei Kemenkes menunjukkan bahwa lebih dari 33% masyarakat Indonesia kurang beraktivitas fisik, menjadikan mereka rentan terhadap penyakit metabolik. Di tengah kekhawatiran ini, muncul sebuah fenomena sederhana namun berdampak besar yaitu gerakan 5000 langkah per hari sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerakan ini bukan hanya menjadi langkah kecil sebagai upaya pencegahan terhadap diabetes, tetapi juga sejalan dengan visi global untuk membangun masyarakat yang lebih sehat dan berkelanjutan melalui tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).
Keluarga merupakan struktur lapisan masyarakat terkecil dan yang utama. Pergeseran dalam dinamika keluarga karena adanya perubahan sosial memunculkan peran baru perempuan sebagai kepala keluarga. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023) tentang Data Perempuan Kepala Keluarga berdasarkan Wilayah Tahun 2017 – 2023, perempuan yang menjadi kepala keluarga disebabkan oleh adanya adaptasi terhadap hasil dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Fenomena tersebut memunculkan tantangan baru yaitu seringkali terdapat diskriminasi dalam pembangunan yang menyebabkan pengakuan terhadap hak dan kekuasaan perempuan sebagai kepala keluarga lebih terbatas jika dibandingkan dengan laki-laki.
Tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya poin nomor 5 (kesetaraan gender) tidak akan tercapai tanpa adanya komunikasi efektif untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat didalamnya. Salah satu caranya dapat dilakukan melalui pendekatan Theatre for Development (TfD) untuk membangkitkan partisipasi masyarakat. Sebagai medium komunikasi pembangunan, TfD didukung oleh adanya proximity dan kebutuhan hiburan yang bernuansa “lokal” sehingga menjadi modal awal untuk mensosialisasikan beragam isu pembangunan kepada masyarakat. Pendekatan TfD dalam masyarakat bisa dimanfaatkan untuk membedah sejarah budaya pada seni pertunjukan rakyat.
Setiap menjelang hari raya, fenomena pemulung dan pengemis musiman kembali menjadi sorotan publik karena jumlahnya yang tiba-tiba meningkat di berbagai kota besar di Indonesia. Mereka datang dari berbagai daerah, bermigrasi ke kota-kota besar dengan harapan memperoleh sedekah dari masyarakat yang sedang merayakan hari kemenangan. Meskipun hal ini tampak sebagai fenomena sosial tahunan, keberadaan mereka menimbulkan dilema sosial dan kebijakan, khususnya dalam konteks urbanisasi, kesejahteraan, dan pengelolaan ruang kota. Fenomena ini tidak hanya menyangkut aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga beririsan langsung dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan 1 (tanpa kemiskinan), tujuan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), dan tujuan 11 (kota dan permukiman yang berkelanjutan). Perlu dilakukan analisis mengenai penyebab dan dampak dari fenomena ini serta rekomendasi kebijakan berbasis SDGs untuk penanganannya.