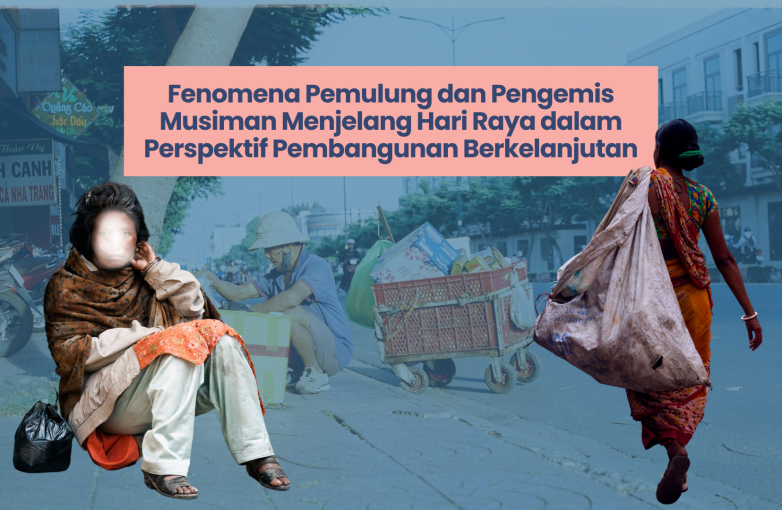
Setiap menjelang hari raya, fenomena pemulung dan pengemis musiman kembali menjadi sorotan publik karena jumlahnya yang tiba-tiba meningkat di berbagai kota besar di Indonesia. Mereka datang dari berbagai daerah, bermigrasi ke kota-kota besar dengan harapan memperoleh sedekah dari masyarakat yang sedang merayakan hari kemenangan. Meskipun hal ini tampak sebagai fenomena sosial tahunan, keberadaan mereka menimbulkan dilema sosial dan kebijakan, khususnya dalam konteks urbanisasi, kesejahteraan, dan pengelolaan ruang kota. Fenomena ini tidak hanya menyangkut aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga beririsan langsung dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan 1 (tanpa kemiskinan), tujuan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), dan tujuan 11 (kota dan permukiman yang berkelanjutan). Perlu dilakukan analisis mengenai penyebab dan dampak dari fenomena ini serta rekomendasi kebijakan berbasis SDGs untuk penanganannya.

Keberadaan pemulung dan pengemis musiman menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang belum tersentuh program pengentasan kemiskinan secara optimal. Mobilitas mereka bersifat musiman, tetapi justru mencerminkan kesenjangan ekonomi dan ketidakstabilan pendapatan di daerah asal mereka. Hal ini berkaitan dengan tujuan 1 SDGs yaitu tanpa kemiskinan. Selain itu, terkadang banyak dari pengemis dan pemulung musiman ini tidak memiliki keterampilan kerja yang memadai. Kurangnya akses terhadap pekerjaan layak mendorong mereka mengambil pilihan yang bersifat informal dan rentan, tanpa jaminan sosial maupun kepastian pendapatan. Realita yang ada berkaitan dengan tujuan 8 SDGs mengenai pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Disisi lain, urbanisasi musiman ini juga menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan tekanan terhadap fasilitas kota, termasuk tempat tinggal, sanitasi, dan ketertiban umum. Tanpa regulasi dan pengelolaan yang baik, hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup di perkotaan seperti tujuan 11 SDGs tentang kota dan permukiman yang berkelanjutan.
Beberapa faktor utama yang mendorong munculnya pemulung dan pengemis musiman, antara lain karena adanya ketimpangan pembangunan desa-kota, minimnya lapangan kerja di daerah asal, tradisi memberi sedekah menjelang lebaran/hari raya, serta lemahnya sistem jaminan sosial dan perlindungan sosial di daerah terpencil. Fenomena tahunan ini menimbulkan dampak di bidang sosial dan juga ekonomi. Di bidang sosial, stigma terhadap golongan kurang mampu kian meningkat dan kota justru dianggap menjadi kurang nyaman bagi warga dan wisatawan. Dalam bidang ekonomi, aktivitas informal yang tidak terkelola dapat mengganggu estetika dan kenyamanan lingkungan usaha.
Untuk itu, diperlukan penguatan basis data sosial oleh pemerintah daerah guna melakukan pendataan yang komprehensif terhadap masyarakat golongan rentan agar bantuan sosial tepat sasaran. Pemberdayaan ekonomi desa melalui program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan berbasis potensi lokal agar masyarakat tidak bergantung pada urbanisasi musiman juga perlu dipertimbangkan. Regulasi dan edukasi publik juga tidak kalah penting agar masyarakat memahami cara memberi bantuan sosial secara terstruktur dan dapat efektif mengurangi praktik mengemis di jalan. Namun yang terpenting adalah adanya kolaborasi dan sinergi lintas sektor antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta dalam menciptakan program inklusif berbasis SDGs.
Pada intinya, fenomena pemulung dan pengemis musiman bukan hanya permasalahan sosial tahunan, tetapi merupakan refleksi dari ketimpangan struktural dalam pembangunan. Dalam kerangka SDGs, penanganan isu ini memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pemberdayaan ekonomi, pembangunan inklusif, serta penataan kota yang berkelanjutan. Hanya dengan kerja sama lintas sektor dan kebijakan yang tepat sasaran, Indonesia dapat mendekatkan diri pada tercapainya pembangunan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Penulis dan Reviewer: Tim Prodi PKP Pascasarjana UGM
